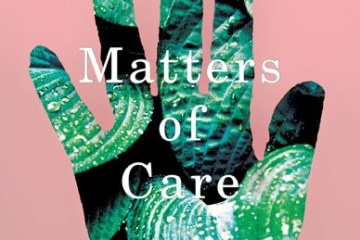Bisakah Non-Eropa Berpikir? Eurosentrisme dan Perebutan Ruang Otoritas Pengetahuan
 Dabashi, Hamid. Can Non-Europeans Think? [Bisakah Non-Eropa Berpikir?]. London: Zed Books, 2015.
Dabashi, Hamid. Can Non-Europeans Think? [Bisakah Non-Eropa Berpikir?]. London: Zed Books, 2015.
“Fuck You, Walter Mignolo!” – Slavoj Zizek
Buku yang terbit pada tahun 2015 ini adalah rekaman dari polemik yang dialami Hamid Dabashi, seorang pemikir poskolonial dengan beberapa filsuf Eropa pada tahun 2013. Pemicunya adalah sebuah artikel yang Dabashi tulis untuk merespons artikel lainnya yang ditulis oleh Santiago Zabala dengan judul “Slavoj Zizek and The Role of Philosopher”. Tanpa disangka, artikel Dabashi mendapat banyak sorotan, termasuk kritik dan olokan dari pihak-pihak yang tidak sependapat dengannya. Meski begitu, tak sedikit juga yang sependapat; Walter Mignolo dan Aditya Nigam adalah dua di antaranya (40).
Dalam artikel Zabala tersebut, Dabashi melihat riak-riak eurosentisme dan pengekalan cara pandang imperial. Hal ini bisa dimaklumi. Sebagai salah seorang pemikir poskolonial, Dabashi mengakrabi banyak model tulisan dan karya yang menyimpan tendensi kolonialistik. Termasuk juga, dia terbiasa mengawasi dengan cermat letupan-letupan orientalistik yang bergerak di bawah upaya-upaya monopoli kebenaran, termasuk monopoli otoritas yang sepertinya muncul dalam tulisan Zabala.
Santiago Zabala dalam artikelnya tersebut menulis,
“Ada banyak filsuf penting dan aktif hari ini ini: Judith Butler di Amerika Serikat, Simon Critchley di Inggris, Victoria Camps di Spanyol, Jean-Luc Nancy di Prancis, Chantal Mouffe di Belgia, Gianni Vattimo di Italia, Peter Sloterdijk di Jerman dan Slavoj Zizek di Slovenia, belum lagi mereka yang ada di Brasil, Australia, dan Cina.” (63)
Pada bagian pertama bukunya, Hamid Dabashi mengupas artikel Santiago Zabala. Sebagaimana yang tergambar dari satu potong paragraf di atas, Zabala secara tidak sadar ditengarai telah mengidap penyakit eurosentrisme. Dalam konteks signifikansi “filsafat hari ini”, Zabala dengan rinci menyebut para filsuf Eropa dan tampaknya tidak merasa penting untuk melakukan hal yang sama dalam konteks non-Eropa. Ya, Zabala memang menyebut Brazil dan Cina, akan tetapi tak satupun nama filsufnya yang disebut di sana (64).

Hamid Dabashi
Masalah yang tampaknya sepele ini menjadi problem serius bagi Dabashi. Potongan paragraf dalam artikel tersebut adalah penampakan bagaimana eurosentrisme masih berupaya merebut otoritas dan universalitas. Apa yang dinamakan “filsafat hari ini” adalah filsafat Eropa itu sendiri. Konsekuensi lainnya menurut Dabashi adalah, hari ini, filsafat orang Eropa disebut “filsafat”, sedangkan filsafat Islam atau non-Eropa disebut “etno-filsafat” (66). Ada perbedaan pengakuan perihal posisi di sini. Eropa mendaku dirinya sebagai subyek pertama dan aktif, sekaligus menegaskan kalau non-Eropa lebih pantas diposisikan sebagai obyek yang pasif.
Dengan demikian, ini bukan lagi soal filsufnya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Michael Marder (44), tetapi soal praktik berfilsafat yang punya tendensi superior, yakni seolah-olah tanpanya, tidak akan ada satu pemikiran pun yang dipandang bisa mencapai universalitas atau mendaku universal (64). Lebih jauh lagi, praktik berfilsafat semacam ini hanya mungkin lahir dalam sebuah iklim yang mewarisi keangkuhan imperial; terbiasa mendominasi dan mengambil alih suara-suara pinggiran yang berusaha terdengar.
Sebagaimana yang diakuinya, Dabashi memposisikan dirinya sebagai generasi pemikir pascakolonial. Baik dirinya maupun Mignolo mewarisi bahasa dan sistem kebudayaan yang sepenuhnya terinfeksi kehadiran kolonialisme (43). Karena itulah, Dabashi selalu menggunakan sudut pandang pascakolonial untuk memeriksa setiap sistem pengetahuan yang bekerja, yang melibatkan secara intensif relasi Barat-Timur. Dan untuk ini, Dabashi seringkali harus berterima kasih kepada Edward Said. Kontribusi dan pengaruh Said bagi tumbuhnya tradisi pembacaan kritis pascakolonial diurainya dalam bagian kedua buku ini (74).
Dalam bagian kedua, Dabashi menapaktilasi Edward Said (74-87). Dia bercerita bagaimana dirinya bertemu Said dan gagasannya dalam Orientalism (75-76). Said digambarkan oleh Dabashi sebagai teman, guru sekaligus sosok heroik (79). Bagi Dabashi, Said telah membukakan pintu untuk penemuan diri bagi banyak orang “kulit cokelat” yang selama berabad-abad telah kehilangan identitasnya. Said memberikan kepercayaan diri dan harapan, bahwa mereka juga bisa bersuara dengan lantang; mereka bisa berbicara atas nama dirinya sendiri, berpijak dengan kaki di atas tanah mereka sendiri (77). Studi poskolonial yang digagas Said telah menjadi pintu bagi tumbuhnya kesadaran pascakolonial dalam diri intelektual bangsa-bangsa dunia ketiga, termasuk Dabashi.
Satu kesalahan yang kerapkali bercokol dalam pikiran Barat adalah bayangan bahwa Timur-Tengah dan dunia ketiga masih begitu-begitu saja. Mereka tidak pernah berubah sejak leluhur mereka menginjakkan kaki di sana. Pada bagian ketiga, dengan menjadikan Iran sebagai contohnya, Dabashi memperlihatkan bagaimana dinamika sosial-politik yang terjadi di Timur-Tengah bergerak dengan sangat dinamis, bahkan cenderung radikal (88). Ekses-ekses dan benturan-benturan yang seringkali terjadi, di satu sisi, memang tampak mendekatkan mereka kepada jurang konflik dan krisis elektoral (120). Namun, diakui atau tidak, letupan-letupan problematika yang terjadi di Timur-Tengah telah menempa satu konstruksi kebudayaan yang memungkinkan mereka melahirkan para intelektual organik yang punya kesadaran dan aktualitas diri berikut kontur intelektualisme yang progresif. Dan kenyataannya, dampaknya tidak hanya bisa dirasakan dalam konteks Timur-Tengah, tapi juga oleh Eropa dan dunia secara umum.
Kata Dabashi;
“Pagi telah pecah, dan ada banyak pawai sederhana dari pemuda di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, khususnya di sepanjang daratan Arab dan Muslim; semuanya mengenakan bandana hijau, dapat berbuat untuk saudara dan saudari mereka yang dibungkam di Iran. Mereka telah menyanyikan lagu asli mereka. Dan mereka tengah menunggu paduan suara global.” (122)
Apa yang terjadi di Iran, Palestina dan wilayah lain di Timur Tengah tidak hanya membangkitkan kesadaran lokal, tapi juga telah sedikit menggerakkan kesadaran global. Relasi antara Barat dan Timur juga tidak lagi seketat dulu, tetapi sudah mulai cair dan gembok-gembok pintu yang selama berabad-abad ditutup, kini secara perlahan mulai dibuka. Dengan kalimat lain, apa yang tampak di depan mata bukanlah praktik monopoli dan saling mendaku diri sebagai yang paling global serta universal. Yang ada justru kenyataan bahwa dunia bergerak ke arah keragaman dan multikulturalisme. Dalam keberagaman ini, dialog bebas tendensi yang dilakukan dengan merdeka serta tulus adalah kuncinya.
Pada bagian keempat, Dabashi kemudian mencoba membaca realitas yang terjadi di Timur-Tengah, seperti di Mesir, Iran, Syiria maupun wilayah lainnya (141). Pada wilayah-wilayah ini, Dabashi ingin memperlihatkan bahwa faktor pendorong dinamika sosial-politik tidaklah tunggal. Terdapat hal-hal yang harus disyukuri, dan ada juga hal-hal yang harus diperbaiki. Dabashi mengakui bahwa hambatan bagi kemerdekaan dan kedamaian di Timur Tengah tidak hanya lahir dari faktor-faktor eksternal, seperti kehadiran bangsa-bangsa adidaya yang ikut campur urusan geopolitik sebuah negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kegagalan dalam memaknai tradisi, mendefinisikan eksistensi mereka di hadapan modernitas, yang pada akhirnya berefek pada perbedaan cara memandang serta menjalankan agenda-agenda kebudayaan, politik, sosial dan ekonomi. Perbedaan tersebut tak jarang berakhir pada perang saudara.
Selain itu, bagi Dabashi, perang yang kita saksikan kini bukan hanya sekadar perang fisik. Lebih krusial dari itu, perang yang terjadi adalah perang pengetahuan (265). Pengetahuan tentang apa? Ya tentang Timur Tengah dan Arab. “Siapa mereka?” “Mengapa mereka seperti itu?” “Dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalahnya?” adalah pertanyaan-pertanyaan yang nyatanya tidak hanya dipikirkan oleh orang Arab, tetapi juga orang di luar Arab. Bahkan dalam beberapa kasus, jawaban yang berasal dari intelektual non-Arab seringkali dianggap lebih otoritatif dibanding penjelasan yang coba diuraikan oleh orang Arab sendiri tentang masalah mereka sendiri. Tidak hanya di Arab, rezim pengetahuan semacam ini juga terjadi dalam konteks bangsa-bangsa pascakolonial.
Apa yang dipikirkan Hamid Dabashi dalam “Can Non-Europeans Think?” dan polemiknya dengan para filsuf Eropa merupakan gambaran betapa relasi Timur-Barat belum sepenuhnya cair. Kita masih melihat adanya tendensi eurosentrisme untuk memposisikan diri sebagai “yang universal”. Kita tidak sedang berbicara urusan sekadar kutip-mengutip referensi, tetapi lebih dari itu, masalah akan menjadi gawat kala universalisme rezim pengetahuan Eropa dijadikan alat untuk membenarkan segala bentuk invansi dan perang yang diinisasi Eropa untuk mencaplok wilayah-wilayah lain.
Hari ini, hal semacam itu bisa kita saksikan langsung ketika misalnya The New York Times dan media Barat dengan mudahnya memakai “Dies (mati)” dan “Killed (terbunuh)” ketika mengabarkan tertembaknya Jurnalis Palestina Shireen Abu Akleh oleh peluru Israel. Nama sang korban terpampang lengkap, tidak dengan nama penembaknya. Biarkan si pelaku tetap misterius, dan biarkan kebenaran tertutupi selamanya.