Laut yang Pasang dan Infrastruktur yang Gagal
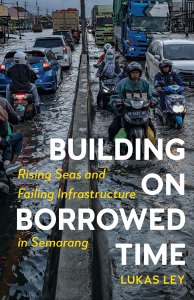 Ley, Lukas. 2021. Building on Borrowed Time: Rising Seas and Failing Infrastructure in Semarang (Membangun dalam Ketidakpastian: Naiknya Permukaan Laut dan Kegagalan Infrastruktur di Semarang). Penerbit Universitas Minnesota.
Ley, Lukas. 2021. Building on Borrowed Time: Rising Seas and Failing Infrastructure in Semarang (Membangun dalam Ketidakpastian: Naiknya Permukaan Laut dan Kegagalan Infrastruktur di Semarang). Penerbit Universitas Minnesota.
Sebagian besar daerah Semarang Utara, termasuk Kemijen yang menjadi lokasi penelitian Lukas Ley, dibangun di atas lahan basah yang terus mengalami penurunan signifikan (10-15 cm) per tahun. Air sungai yang beracun mengalir dari saluran pembuangan dan membanjiri rumah warga, membawa serta ancaman penyakit dan kerusakan harta-benda. Ada kalanya, air payau buangan ini terperangkap di rumah-rumah dan selokan-selokan alih-alih mengalir terus menuju tujuan akhir: Sungai Banger. Bahaya yang menghantui ini mendefinisikan kekinian warga, memaksa mereka untuk terus-menerus merancang strategi dan berimprovisasi dengan solusi jangka pendek. Peristiwa banjir jarang mengusik ritme keseharian warga, melainkan hanya ditanggapi dengan aktivitas pemompaan berkala. Dalam Building on Borrowed Time, Ley berargumen bahwa semua upaya pencegahan warga ini berjangkar dalam sebuah temporalitas yang dinamakannya sebagai masa kini kronis.
Cara spesifik dalam mengalami waktu ini, di mana warga dihadapkan pada kemungkinan konstan akan kegagalan infrastruktural dan banjir aktual, membentuk relasi mereka dengan masa depan dalam cara yang juga spesifik. Warga tersosialisasikan ke dalam sebuah kekinian yang selalu dibayang-bayangi risiko bencana. Mereka lantas menyikapinya dengan secara mandiri memperbaiki dan membangun ulang infrastruktur. Hal ini tidak boleh sekadar dipahami sebagai sikap berdikari dari sebuah populasi yang menyadari bahwa mereka berdiam di ekologi tertentu; melainkan, mesti dipandang sebagai produk dari proses eksklusi politik yang bisa dilacak sampai era kolonial. Bagi Ley, saat ini korban banjir terjebak dalam sebuah dunia yang semata berfokus pada kekinian karena aneka perbaikan tidak membuka ruang potensial bagi masa depan yang lebih visioner.
Sebagai tambahan, seringkali tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas infrastruktur: komunitas lokal, lembaga swasta, atau negara. Warga sendiri berhubungan dengan aneka macam aktor, yang pada gilirannya menyediakan pendanaan untuk usaha-usaha perbaikan dan pemeliharaan. Tapi, siklus pendanaan yang tidak konsisten ini tentu menghasilkan usaha-usaha yang juga tidak konsisten. Belum lagi jika kita menimbang aneka isu lain, misalnya peningkatan harga diesel yang tidak sebanding dengan dana yang dimiliki warga. Meski begitu, bagi Ley, usaha-usaha ini tetaplah penting jika kita membacanya sebagai realitas etnografik yang memaksa kita untuk menimbang sebuah masa depan yang terkubur dalam masa kini yang seolah abadi. Penuturan etnografik berpotensi mendokumentasikan usaha-usaha manusia untuk hidup bersandingan dengan bentuk-bentuk dominan pengetahuan dan kekuasaan dalam sebuah dunia yang rentan, sesekali mengusiknya atau menghindarinya sembari terus berjuang untuk hidup dengan waktu pinjaman.
Isi Buku
Bab 1 mengajak kita berkenalan dengan permukiman di kawasan rawa pesisir Semarang Utara, dengan argumen bahwa industrialisasi pesisir Semarang dan ekspansi sistem kereta api Jawa di akhir abad ke-19 menghasilkan dan meningkatkan permintaan tenaga kerja, tapi juga sekaligus mendesak migran-migran rural ke dalam ceruk-ceruk sosioekologis. Tak diterima di permukiman-permukiman orang Belanda dan Tionghoa (yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan), migran-migran ini mulai menghuni dan menggarap lahan basah untuk keperluan agrikultur. Kemunculan permukiman-permukiman spontan ini (yang dirujuk sebagai ‘kampung’) menghasilkan pemisahan geografis antara “rawa pribumi di utara” dan “kawasan kosmopolitan di selatan”, sebuah pemisahan yang terus dianut oleh politik urban Semarang sampai hari ini. Dalam konteks ini, banjir yang dialami oleh wilayah utara tidak hanya dipahami secara harfiah sebagai peristiwa atau bencana, tapi juga menyimbolkan sebuah ekses, yakni: wilayah utara sebagai sumber keberlebihan air, populasi, limbah, sampah, dan kejahatan. Dengan kata lain, wilayah utara terancam tapi sekaligus juga ancaman bagi pihak lain.

Lukas Ley
Bab 2 menggambarkan intervensi pemerintah, khususnya pada era Orde Baru. Selama kurun 1970-an yang ditandai lonjakan ekonomi, Semarang mengalami urbanisasi yang masif. Karena proses ini sama artinya dengan perpindahan manusia dari utara ke selatan, kampung-kampung di utara secara dikotomis mulai dianggap sebagai sarang masalah yang dikuasai para penjahat, sebagai oposisi dari selatan (baca: sumber segala yang baik). Orde Baru berusaha mengontrol kampung-kampung ini melalui normalisasi sungai (pelebaran dan penanggulan sungai), yang dibarengi pengusiran dan penggusuran. Normalisasi sungai adalah cara menjadikan kampung lebih transparan (baca: teramati dan terkontrol oleh birokrasi) sekaligus upaya mencitrakan kebersihan dan modernitas kampung (baca: upaya menyempitkan gap antara kampung dan kota). Kebijakan ini, bagi Ley, adalah penjelmaan dari ideologi pembangunan yang mempromosikan modernisasi sebagai tujuan universal untuk semua dengan melakukan patologisasi atas sebuah seksi populasi.
Bab 3 menuturkan bentuk kehidupan sehari-hari di Semarang Utara saat ini dari perspektif pengalaman banjir yang permanen dan berulang. Karena air secara rutin mendobrak batas-batas material kediaman dan menggenang di jalanan kampung dan rumah-rumah, warga mulai berorganisasi secara mandiri (baca: mengambil alih tugas krusial pemerintah, yang secara ideologis dibenarkan oleh imbauan tentang partisipasi akar rumput) untuk menangani masalah ini, utamanya melalui pengadaan pompa-pompa dan pembentukan asosiasi-asosiasi pemompaan untuk memulihkan aliran air. Di sini, banjir menjadi denyut yang menunjang kehidupan ekonomi, sosial, dan afektif individu. Krisis yang berulang memang pada akhirnya mendatangkan infrastruktur baru dan proyek-proyek pembangunan komunitas. Namun, semua program ini terbukti hanya menjadi usaha tambal-sulam yang datang dan pergi silih-berganti alih-alih intervensi yang esensial.
Bab 4 menunjukkan bagaimana sensibilitas warga pada hidrologi dipengaruhi oleh keadaan politik yang terus berubah-ubah. Dengan menanyakan apa makna dari menjadi subjek politik di Semarang – kota yang dipuji oleh World Bank atas gaya pembangunan akar rumputnya tapi sekaligus dibayangi ancaman perubahan iklim – bab ini berfokus pada proyek-proyek pembangunan skala RT/RW dan pergumulan konstan untuk mencari pendanaan di level pemerintahan kota dan provinsi. Dana yang cair sebagian besar dipakai untuk memperbaiki jalan dan infrastruktur kampung, dan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan. Di sini, Ley berargumen bahwa infrastruktur pelan-pelan mengalami pergeseran makna. Lapis demi lapis blok batu yang dipakai untuk meninggikan infrastruktur agar lebih kebal banjir tidak lagi dipahami oleh warga sebagai “pembangunan”, tapi semata, secara harfiah, sebagai “peninggian”. Jika “pembangunan” berasosiasi dengan proyek kebangsaan, maka “peninggian” menyiratkan sebuah konteks yang sementara dan lebih bercorak kekinian, di mana warga pesisir di Semarang dapat mengapung di atas air untuk sementara waktu.
Bab 5 mengkaji proyek antibanjir yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, pemerintah kota Semarang, dan pakar air dari Rotterdam, Belanda. Kerja sama bilateral ini, terlepas dari perubahan transformatif-modernis yang dijanjikannya, pada akhirnya hanya memperkuat ketergantungan pada solusi-solusi teknis. Dengan bersandar pada pengetahuan saintifik Barat dan berabad-abad pengalaman mengelola air, kedatangan para pakar dari Belanda – dengan teknik andalan mereka yang dinamakan “polder” – dibarengi dengan iming-iming perubahan progresif. Kenyataannya, “polder” hanya menjadi solusi yang murni teknis, dengan efek konkret yang memang terbukti (baca: mampu mengeringkan air dengan lebih efektif dan efisien) tapi tanpa menginspirasi perubahan signifikan ihwal tata-cara manajemen air di Semarang. Bahkan faktanya, durasi operasional “polder” diramalkan hanya akan bertahan selama 15 tahun berhubung frekuensi penurunan lahan di Semarang yang meningkat pesat. Dengan demikian, warga – yang diajari untuk bersikap selayaknya warga negara yang terberdayakan – sekali lagi menemukan diri mereka terjebak dalam masa kini kronis, di mana krisis dikelola oleh pemerintah dan agensi-agensinya yang tidak akuntabel. Di sisi lain, para politisi kini bisa lepas tangan karena mengklaim bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan masalah banjir. Di sini, Ley berspekulasi bahwa kondisi kronis yang sebenarnya dialami warga bukanlah banjir berkala, melainkan hegemoni normalisasi yang dipaksakan oleh pemerintah.
Adakah jalan keluar?
Studi Ley menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di pesisir utara Semarang: durasi infrastruktur, aktivitas pemeliharaan warga, intervensi pemerintah, dan temporalitas banjir. Jadi, banjir tidak bisa dijelaskan semata oleh perubahan iklim belaka, ataupun kemiskinan (material maupun intelektual), ataupun kegagalan pembangunan. Alih-alih, ideologi dari skema-skema perbaikan yang dirancang oleh otoritaslah yang ternyata menghasilkan sebuah masa kini yang kronis, sebuah lokasi temporal yang dibayang-bayangi oleh risiko dan miskin transformasi politik.
Apa yang bisa dilakukan negara-negara neoliberal saat ini untuk melindungi warganya yang tinggal di zona-zona yang terancam perubahan iklim, di mana kekacauan tidak pernah berevolusi menjadi tatanan melainkan sekadar bermutasi menjadi bentuk yang baru? Terlepas dari fakta bahwa perubahan iklim sudah dirasakan dengan sangat konkret oleh mayoritas penduduk bumi, mayoritas pemerintah di dunia masih berpura-pura bahwa ini adalah ancaman yang masih jauh dan bisa ditangani secara kasual, atau dengan kata lain, secara reaktif alih-alih visioner. Masa kini kronis yang dihasilkan oleh kemasabodohan ini tidak hanya menjadi sumber bencana berkala, tapi juga kebuntuan politik yang mencerabut orang-orang dari masa depan yang lebih bermartabat.
Salah satu informan Ley berkomentar bahwa barangkali tindakan terbaik yang bisa dilakukan adalah sekalian saja membiarkan dunia ini tenggelam, membiarkan laut mencaplok daerah hunian warga berikut seisinya. Jika kita mempertimbangkan masa kini kronis sebagai efek dari marjinalisasi politik, maka komentar ini bisa ditanggapi secara serius sebagai satu-satunya janji yang bisa ditawarkan oleh masa depan di hadapan kemangkrakan infrastruktural yang dialami warga.


