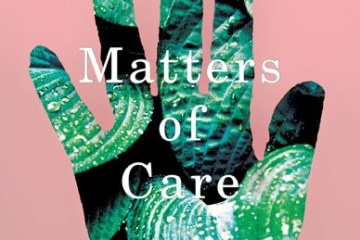Muslimah di Persimpangan: Pendidikan, Gender, dan Ekonomi-Politik di Pakistan
 Khoja-Moolji, Shenila. 2018. Forging the Ideal Educated Girl: The Production of Desirable Subjects in Muslim South Asia [Menempa Perempuan Terdidik Ideal: Produksi Subjek yang Berhasrat dalam Konteks Muslim di Asia Selatan]. Penerbit Universitas California
Khoja-Moolji, Shenila. 2018. Forging the Ideal Educated Girl: The Production of Desirable Subjects in Muslim South Asia [Menempa Perempuan Terdidik Ideal: Produksi Subjek yang Berhasrat dalam Konteks Muslim di Asia Selatan]. Penerbit Universitas California
Pada tahun 2012 lalu, benak publik jelas tak akan lupa dengan insiden penembakan yang menimpa Malala Yousafzai, seorang remaja perempuan Muslim dari Pakistan. Kejadian ini sempat menggegerkan banyak pemimpin negara dan badan organisasi dunia yang kemudian mengekspresikan dukungan kepada Malala. Dua tahun kemudian, pada April 2014, organisasi militan Boko Haram asal Nigeria menculik 300 murid perempuan yang tinggal di sekolah asrama di Chibok, Nigeria. Walaupun terdapat banyak bukti bahwa murid laki-laki juga ikut diculik, banyak media massa Barat saat itu spontan mengaitkan insiden penculikan ini dengan sikap Boko Haram yang anti dengan pendidikan bagi perempuan.
Dalam perkembangannya, insiden militanisme Boko Haram ini kemudian dikaitkan dengan isu tentang pentingnya penyediaan akses pendidikan bagi perempuan. Beberapa pemimpin negara, seperti mantan perdana menteri Australia Julia Gillard, tidak segan mengaitkan kejadian Boko Haram ini dengan kekerasan yang menimpa Malala. Singkatnya, bagi kelompok ekstremis, pendidikan bagi perempuan adalah sesuatu yang berbahaya. Asumsi semacam ini kerap diasosiasikan dengan budaya patriarki yang dianggap sebagai salah satu fitur utama dari negara-negara “Global South (Selatan Dunia)”, seperti Pakistan dan Nigeria.
Buku karya Shenila Khoja-Moolji, Forging the Ideal Educated Girl: The Production of Desirable Subjects in Muslim South Asia (2018), mengupas bagaimana isu pendidikan perempuan di Pakistan selalu berkelindan dengan isu nasionalisme, struktur kelas, dan juga masyarakat patriarkal. Sebelum buku ini terbit, Khoja-Moolji memang sudah banyak meneliti isu seputar perempuan, agama, pendidikan, dan kelas di Pakistan. Buku ini merupakan perpanjangan dari sejumlah artikel jurnal yang ia tulis, disertai dengan tambahan analisis baru yang menilik representasi perempuan dalam iklan dan acara televisi serta focus group discussion (FGD) yang ia lakukan. Semua ini ia sajikan dengan meninjaunya dari perspektif feminisme pascakolonial.
Buku ini terdiri atas enam bab. Pada bab pertama, Khoja-Moolji menjelaskan diskursus tentang konstruk pendidikan yang ideal bagi perempuan di Pakistan dengan menghadirkan kembali peristiwa penembakan Malala Yousafzai dan wacana yang mengitarinya. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pendidikan di Pakistan modern, Khoja-Moolji mengajak pembaca untuk menilik kembali wacana-wacana apa saja yang selalu terikat dengan pendidikan perempuan di Pakistan pada abad ke-19. Saat itu, Pakistan belum merdeka dan masih merupakan bagian dari Kerajaan Mughal. Dari riset yang ia himpun, Khoja-Moolji berargumen bahwa pemindahan kekuasaan dari Kerajaan Mughal ke India di bawah pemerintahan kolonial Inggris memicu kecemasan akan status kelas di antara banyak elite Muslim.

Shenila Khoja-Moolji
Setelah terjadinya pemberontakan pada tahun 1857, status para elite dan aristokrat Muslim semakin terancam karena pemerintah Inggris memberikan lebih banyak dukungan kepada umat Hindu, sedangkan dukungan untuk umat Muslim semakin surut. Para elite Muslim ini sering disebut sebagai kaum ashraf yang terdiri atas orang-orang Muslim aristokrat keturunan Arab, Persia, Turki, dan Afghanistan. Selain khawatir karena dukungan untuk kaumnya semakin surut, kaum ashraf juga harus menghadapi realita baru dengan munculnya kaum ashraf baru—yang didominasi oleh para pedagang—yang direproduksi oleh institusi-institusi pendidikan di bawah pemerintahan Inggris. Mobilitas kelas yang dijanjikan oleh institusi pendidikan ini melahirkan ide meritokrasi bahwa siapapun yang bekerja keras akan dapat menaikkan derajat kelasnya. Di sisi lain, muncul juga ide tentang kehormatan (respectability) yang berkaitan erat dengan bagaimana ke-ashraf-an seseorang bisa dinilai dari praktik sosialnya.
Pada bab kedua, Khoja-Moolji menunjukkan bagaimana institusi pendidikan di bawah pemerintah Inggris di India—yang lebih berupa sekolah misionaris—mengancam keberadaan sistem pendidikan Islam yang dibangun oleh para kaum Muslim ashraf. Pemerintah Inggris hanya membiayai institusi pendidikan yang menggunakan Bahasa Inggris. Dengan dihapusnya Bahasa Persia sebagai bahasa administrasi pada tahun 1837, status dan posisi kaum Muslim ashraf semakin terpinggirkan.
Inilah konteks yang melatarbelakangi munculnya reformisme Islam pada pertengahan abad ke-19, yang didominasi oleh laki-laki. Selain menyoal tentang pendidikan bagi kaum Muslim secara umum, mereka juga berfokus pada pendidikan perempuan. Hal ini dipicu oleh suatu kesadaran bahwa eksistensi ulama sebagai otoritas moral di ruang publik kian tergerus, sehingga keluarga dan perempuan dipandang memiliki peran yang signifikan bagi pendidikan moral generasi Muslim selanjutnya. Di sini, terdapat dua pertanyaan yang menjadi lokus perdebatan para reformis Muslim: (1) pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh perempuan? Dan, (2) dimanakah perempuan harus menerima pendidikan? Hingga abad ke-20, pertanyaan-pertanyaan semacam ini masih kerap digaungkan. Di antara tokoh Muslim reformis yang menonjol saat itu ialah Mumtaz Ali dan Sultan Mahomed Shah (lebih dikenal dengan Aga Khan III).
Pada abad ke-17 dan ke-18, pendidikan perempuan yang digagas oleh para Muslim reformis ini bertujuan untuk membentuk citra perempuan sebagai istri dan pengurus rumah tangga yang baik. Pandangan bahwa perempuan seharusnya berada di rumah dan peran suami sebagai pencari nafkah ditekankan secara masif. Menurut Khoja-Moolji, pandangan ini merepresentasikan adanya bias kelas. Kaum ashraf percaya bahwa perempuan yang terhormat seharusnya tidak bekerja, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mengharuskan ia untuk bekerja. Sementara itu, perempuan yang bekerja bukan karena terpaksa akan kehilangan status kehormatannya dan menjadi bagian dari kaum ajlan, yakni kaum Muslim yang secara ekonomi lebih rendah dibanding kaum ashraf. Ide tentang kehormatan kelas bagi perempuan lambat laun diamini oleh kebanyakan kaum Muslim. Hal ini ditandai dengan terbitnya novel terkenal karya Nazir Ahmed yang berjudul Mirat-ul-uroos (The Bride Mirror) pada tahun 1869, yang mengisahkan tentang pentingnya menjadi perempuan Muslim terhormat dan sadar akan perannya dalam menjaga kelangsungan status kelasnya.
Lantas, bagaimana dengan wacana pendidikan bagi perempuan di Pakistan pada abad ke-20? Pada bab ketiga, Khoja-Moolji secara rinci membahas perubahan narasi tentang wacana pendidikan perempuan pasca kemerdekaan Pakistan. Dengan status kemerdekaan yang masih baru pada tahun 1947, Pakistan menghadapi beberapa ancaman, seperti perdebatan teritorial dengan India hingga lemahnya struktur demokrasi. Status Pakistan sebagai nation-in-the-making juga membuat para pemimpin negara ini menekankan pentingnya mengartikulasikan makna tentang bagaimana menjadi warga negara Pakistan yang ideal. Pada aras pertautan diskursus tentang nation-building, modernisasi, dan peran agama, wacana perempuan yang terdidik kemudian dimunculkan kembali.
Perempuan modern yang mempunyai semangat nasionalisme tinggi untuk membangun negara dipandang sebagai subjek perempuan yang ideal. Sebaliknya, perempuan konservatif, seperti mereka yang mengenakan purdah (cadar), atau perempuan yang dianggap terlalu modern karena mengadopsi budaya Barat, dipandang sebagai subjek perempuan yang ‘gagal’. Di sini, konstruk kapitalisme bertautan erat dengan pembentukan perempuan terdidik yang ideal. Misalnya, kebijakan tentang pendidikan perempuan pada abad 20 ini lebih mendorong kaum perempuan untuk berpartisipasi sebagai pekerja dan konsumen di sektor formal dan ekonomi. Akibatnya, mereka memikul beban ganda; di satu sisi, status mereka sebagai perempuan terdidik menjadi alat untuk menjaga kehormatan diri, tetapi di sisi lain, mereka juga harus berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi negara.
Pada bab keempat, Khoja-Moolji menunjukkan bahwa narasi-narasi kapitalisme dan neoliberalisme semakin menyetir arus wacana perempuan yang terdidik di Pakistan pada masa sekarang. Dari beberapa FGD yang ia lakukan dengan remaja perempuan di Pakistan pada tahun 2015, Khoja-Moolji berpendapat bahwa pendidikan bagi perempuan bisa menjadi alat untuk memberdayakan diri atau justru menjadi beban tambahan.
Bagi perempuan kelas menengah, pendidikan adalah jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan kantoran. Bekerja di luar rumah juga bukan sesuatu yang tabu lagi karena bekerja dikaitkan dengan dukungan terhadap pembangunan negara. Namun tidaklah demikian bagi perempuan dari kelas elite. Bagi mereka, pendidikan dikonsumsi semata-mata untuk mendapatkan calon suami yang lebih baik. Di sini, pendidikan lebih diposisikan sebagai suatu praktik sosial dan komoditas. Sebaliknya, bagi mereka yang kurang beruntung, pendidikan adalah beban finansial bagi keluarga. Mereka percaya dengan janji pendidikan sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak—sebuah mimpi untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.
Pada bab kelima, Khoja-Moolji membahas peran signifikan dari munculnya telenovela Mirat-ul-Uroos di Pakistan pada tahun 2011 dan 2012 dalam merepresentasikan citra perempuan ideal terdidik. Seperti namanya, telenovela ini adalah adaptasi dari novel Nazir Ahmed dengan judul yang sama. Meskipun ide-ide tentang agama, kelas, dan gender di Pakistan berubah seiring zaman, gagasan tentang perempuan ideal terdidik direproduksi dalam telenovela Mirat-ul-Uroos ini. Lewat dua protagonis perempuan yang mempunyai sifat yang berbeda, penonton disajikan dengan citra perempuan ideal yang direpresentasikan oleh mereka yang dapat melakukan “beban ganda”. Yakni, perempuan harus dapat berperan penting dalam sistem ekonomi sekaligus tetap secara aktif mempertahankan status kelas menengahnya dengan menerapkan praktik-praktik terkait kehormatan (respectability). Ide tentang respectability ini memiliki arti bahwa perempuan sepatutnya hanya bekerja ketika didesak oleh kebutuhan.
Pada bab keenam, sebagai bab terakhir, Khoja-Moolji menekankan kembali bahwa ide tentang perempuan Muslim terdidik yang ideal di Pakistan hampir selalu mengharuskan sang perempuan untuk dibebani dengan sejumlah peran sekaligus. Peran tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari peran domestik seperti menjadi ibu yang baik, hingga peran publik yang cakupannya lebih besar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi negara, menjaga kelangsungan reproduksi kelas menengah, hingga ikut memberantas kemiskinan dan terorisme.
Meskipun didasarkan pada riset yang mendalam, dalam pandangan saya, karya Khoja-Moolji ini juga memiliki keterbatasan. Terlihat bahwa representasi dan suara perempuan dari kelas bawah di pembahasan yang Khoja-Moolji sajikan terasa kurang mendalam. Khoja-Moolji memang menyebutkan sumber dari perempuan-perempuan kelas bawah di buku ini, namun sumber tersebut tidak digali secara aktif. Keterbatasan ini bisa diatasi dengan mengikutkan remaja perempuan dari kelas bawah dalam sesi FGD yang Khoja-Moolji lakukan. Cukup disayangkan bahwa wawancara FGD yang Khoja-Moolji lakukan pun masih berpusat pada remaja perempuan kelas menengah.
Namun demikian, analisis pascakolonial yang ditawarkan oleh Khoja-Moolji sangatlah bermanfaat untuk melihat interseksi antara isu gender, kelas, agama, dan ekonomi-politik. Pada zaman kiwari, dengan bentuk-bentuk kolonialisme mutakhir yang menganggap bahwa pendidikan modern menjadi standard seberapa ‘modern’ dan ‘terbelakang’-nya seseorang, wacana tentang konstruk perempuan Muslim yang terdidik menjadi arena kontestasi antara apa yang disebut sebagai negara Global South (Selatan Dunia) versus negara Global North (Utara Dunia). Di sini, proyek-proyek modernisasi dari negara-negara Global North untuk memberdayakan perempuan di negara Global South ternyata dijadikan alat untuk mendulang profit kapitalisme. Sebagai contoh, hal ini bisa dilihat dari program SPRING Initiative – kolaborasi antara USAID, Kementerian Pengembangan Internasional Inggris, dan Nike Foundation – yang diimplementasikan di negara-negara Global South.
Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Dalam upayanya untuk menarik perusahaan besar, program ini mengajak para sponsor ikut serta berpartisipasi dalam “membuat peluang-peluang ekonomi dengan praktik inovasi baru.” Tidak hanya itu, untuk menarik para investor, program ini mengklaim bahwa “dengan investasi Anda, SPRING Initiative dapat merangkul peluang sosial terbesar—remaja perempuan—sekaligus memberikan besar asset profit (return of invesment) yang maksimal.” Inisiatif dari SPRING ini seakan memposisikan perempuan-perempuan di Global South sebagai para pekerja dan konsumen yang belum digali potensinya sehingga mereka dipandang layak untuk diberdayakan oleh perusahan-perusahan Barat terkemuka sebagai sponsor mereka melalui program mentorship.
Khoja-Moolji mengaitkan inisiatif dari SPRING ini dengan apa yang disebut dengan triple movement dari New Washington Consensus. Triple movement tersebut didefinisikan sebagai upaya untuk “menopang praktik dan rasionalitas pasar global melalui proyek-proyek sosial-lokal, serta mengakui dan menutupi kegagalan pasar sekaligus mengembangkan subjek pasar baru.” Dalam konteks keruntuhan finansial di Amerika pada tahun 2008 lalu, triple movement dari konsensus tersebut dilandasi dengan suatu pemahaman bahwa perusahan-perusahaan korporat perlu menyasar target baru agar tetap dapat mendulang profit. Cara ini lalu dicapai lewat inisiatif seperti SPRING ini, di mana perempuan menjadi buruh upah rendah dan konsumen yang dimanfaatkan oleh perusahaan lewat klaim pemberdayaan ekonomi.
Pertautan antara pendidikan, gender, dan struktur sosial-ekonomi sebagaimana yang terjadi di dunia pendidikan Pakistan tentu bukanlah fenomena yang unik. Selain itu, bergesernya makna pendidikan, dari instrumen pembebasan manusia menjadi suatu komoditas, bisa saja ditemukan di negara lain, termasuk Indonesia. Misalnya, kebijakan pemerintah saat ini melalui program “Merdeka Belajar” lebih diorientasikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Tujuannya ialah “meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal”. Dalam konteks ini, mahasiswa perguruan tinggi utamanya dipandang sebagai sumber pekerja masa depan yang berharga dalam logika ekonomi neoliberal ini.
Pertanyaan tentang di manakah posisi perempuan dalam kerangka ekonomi neoliberal juga patut direnungkan kembali. Pada satu bagian dalam bukunya, Khoja-Moolji mencatat bahwa di negara-negara maju seperti Amerika Serika, masih banyak perempuan kelas menengah terdidik yang menjadi ibu rumah tangga setelah mereka menikah. Tentunya, hal ini merupakan suatu paradoks bagi sebuah negara yang percaya bahwa pendidikan akan membuat perempuan lebih independen dan mempunyai pilihan hidup yang lebih baik. Lewat bukunya ini, Khoja-Moolji mengajak kita untuk selalu mempertanyakan ulang asumsi-asumsi dasar kita atas pendidikan bagi perempuan.