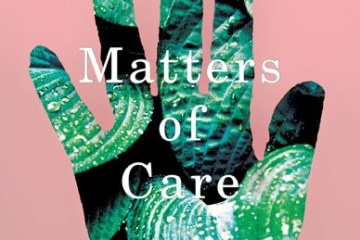Membongkar Senjata Naratif: Analisis Kritis Ghassan Kanafani terhadap Sastra Zionis
 Kanafani, Ghassan. 2022. On Zionist Literature. (Tentang Sastra Zionis). Penerbit Ebb Books.
Kanafani, Ghassan. 2022. On Zionist Literature. (Tentang Sastra Zionis). Penerbit Ebb Books.
Peperangan politik tidak pernah hanya dimenangkan di medan tempur; ia pertama-tama dimenangkan di medan narasi, di dalam pikiran dan imajinasi manusia. Jauh sebelum sebuah negara didirikan atau sebuah perbatasan digambar ulang, fondasi ideologisnya harus terlebih dahulu dibangun melalui bahasa, mitos, dan cerita. Dalam kerangka pemikiran inilah buku Ghassan Kanafani, On Zionist Literature, menemukan urgensi dan kekuatannya yang abadi. Ditulis pada tahun 1967 oleh seorang novelis, jurnalis, dan juru bicara Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), buku ini bukanlah sebuah kritik sastra yang netral dan berjarak. Sebaliknya, ia adalah sebuah tindakan dekonstruksi yang sengit, yakni sebuah upaya intelektual untuk membongkar dan melucuti apa yang Kanafani lihat sebagai senjata naratif utama yang digunakan untuk melegitimasi proyek kolonial Zionis di Palestina. Tesis utamanya—yang ia bangun secara cermat di sepanjang buku—adalah bahwa sastra Zionis bukan sekadar produk sampingan, melainkan pelopor dan prasyarat mutlak bagi Zionisme politik itu sendiri.
Minat akademis utama dalam mengulas buku ini adalah untuk memahami metodologi Kanafani dalam membedah sastra sebagai alat hegemoni. Buku ini menawarkan studi kasus yang impresif tentang bagaimana sebuah gerakan politik secara sadar merekayasa fondasi budayanya sendiri—mulai dari bahasa hingga arketipe pahlawan—untuk mencapai tujuannya.
Secara garis besar, Kanafani menyajikan argumennya sebagai sebuah proses evolusi yang terencana. Ia memulai dari fondasi paling dasar, yaitu bahasa. Dalam bab pertamanya, ia berargumen bahwa bahasa Ibrani secara paksa diubah dari bahasa ritual keagamaan menjadi bahasa nasional yang politis untuk menciptakan ikatan artifisial di antara komunitas Yahudi yang beragam. Proses rekayasa linguistik ini berjalan seiring dengan pembajakan mitos-mitos budaya, seperti yang ia tunjukkan dalam analisisnya terhadap arketipe “Yahudi Pengembara” (The Wandering Jew). Kanafani melacak bagaimana figur cerita rakyat ini diubah dari simbol dosa religius menjadi simbol perjuangan nasionalis, di mana penderitaannya yang abadi memberinya hak moral untuk mengklaim tanah Palestina sebagai akhir dari pengembaraannya.

Ghassan Kanafani
Setelah fondasi bahasa dan mitos diletakkan, Kanafani menyajikan tesisnya yang paling provokatif: Zionisme tidak lahir dari penindasan, melainkan dari privilese. Ia berargumen bahwa pada periode-periode kebebasan dan kesempatan untuk integrasi sosial di Eropa, sebuah kelas elite Yahudi yang kuat secara ekonomi justru menolak asimilasi demi gagasan supremasi rasial. Sastra, menurutnya, menjadi kendaraan utama bagi kelas ini untuk menyebarkan ideologi mereka. Studi kasusnya pada sastra Inggris abad ke-19 sangatlah tajam, di mana ia mengidentifikasi novel Benjamin Disraeli, The Wondrous Tale of Alroy, sebagai karya yang pertama kali melahirkan “pahlawan Zionis” yang rasis, yang kemudian disempurnakan dalam novel George Eliot, Daniel Deronda, yang ia sebut sebagai “Injil Zionis” karena menyediakan cetak biru politik yang canggih.
Dari fondasi ini, Kanafani kemudian membongkar apa yang ia sebut sebagai “Formula Propaganda” yang digunakan secara berulang dalam novel-novel Zionis pasca-1948. Formula ini, yang ia uraikan dalam lima poin sistematis, berfungsi sebagai kerangka untuk membenarkan pengambilalihan Palestina. Formula propaganda yang diidentifikasi Kanafani terdiri dari lima poin berikut.
Pertama, pahlawan penyintas persekusi. Sang pahlawan hampir selalu datang dari Eropa sebagai akibat dari persekusi mengerikan. Dia melarikan diri dari kenangan pembantaian di tangan Hitler, kehilangan keluarga dan teman-temannya, dan mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Dari sanalah aspirasi nasionalisnya muncul untuk memulihkan harga dirinya.
Kedua, kisah cinta penebusan dosa Barat. Pahlawan akan jatuh cinta dengan seorang non-Yahudi, yang tidak mungkin seorang Arab. Hubungan ini menjadi sarana bagi penulis untuk menjelaskan perspektif dan aspirasi Zionis. Hal ini pada akhirnya membuat karakter non-Yahudi tersebut menemukan “rasa tanggung jawab pribadi” atas bencana yang menimpa kaum Yahudi, sehingga ia kemudian mendukung Zionisme sebagai “tindakan penebusan” atas dosa yang dilakukan di tempat lain.
Ketiga, dehumanisasi bangsa Arab. Bangsa Arab, sebagai lawan langsung, digambarkan sebagai individu tanpa tujuan perjuangan yang jelas. Mereka seringkali ditampilkan sebagai tentara bayaran yang melayani kekuatan asing atau tuan tanah feodal. Dengan cara ini, penulis menegaskan keterbelakangan mental dan peradaban bangsa Arab sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Keempat, justifikasi penolakan integrasi. Novel secara terus-menerus menekankan penindasan dunia terhadap kaum Yahudi. Hal ini dibutuhkan sebagai pembenaran mengapa sang pahlawan tidak bisa berintegrasi dengan masyarakat tempat ia berasal dan harus memiliki negara sendiri.
Kelima, pahlawan yang sempurna dan superior. Penulis Zionis menjadikan agama dan ras sebagai faktor internal utama yang mendorong kaum Yahudi ke Palestina, di samping faktor eksternal seperti penindasan dan pembantaian Hitler. Melalui narasi yang seringkali bernada rasis ini, sang pahlawan digambarkan memiliki kompetensi absolut dan menjadi sosok yang sempurna secara mental, fisik, dan historis.
Puncaknya adalah argumen dalam Bab 6 dan 7, di mana ia menunjukkan bahwa formula ini bergantung pada dua pilar rasis: penciptaan pahlawan Yahudi yang maha-sempurna dan superior, yang hanya mungkin ditegakkan melalui dehumanisasi total bangsa Arab. Rasionalisasi utama untuk semua ini, yang ia sebut sebagai “persamaan palsu” yang paling mengerikan, adalah penggunaan tragedi Holocaust sebagai justifikasi moral untuk perampasan hak-hak bangsa Palestina—sebuah bangsa yang tidak memiliki sangkut paut dengan kejahatan Eropa.
Analisis dan Kritik
Sebagai sebuah karya polemik yang bertujuan untuk “mengenal musuh”, buku Kanafani berhasil mencapai tujuannya dengan efektivitas yang brutal. Kekuatan terbesarnya terletak pada metodologi dekonstruksi ideologisnya. Formula lima poin yang ia tawarkan adalah alat analisis yang tajam dan dapat diterapkan untuk membongkar berbagai bentuk propaganda, tidak hanya dalam konteks Zionisme. Kemampuannya untuk mengurai bagaimana narasi superioritas dibangun di atas dehumanisasi “yang lain” adalah inti dari kritik pascakolonial, dan dalam hal ini, Kanafani mendahului karya-karya teoretis seperti Orientalism karya Edward Said.
Lebih dari itu, ketegasan moralnya yang tanpa kompromi memberikan kekuatan pada buku ini. Kanafani tidak ragu-ragu menggunakan istilah “rasis” dan “fasis” karena ia melihat adanya paralelitas secara langsung antara ideologi supremasi rasial dalam sastra Zionis dengan yang ada di Eropa. Analisisnya terhadap penggunaan Holocaust sebagai alat “pemerasan moral” untuk membungkam kritik dan membenarkan kolonialisme adalah argumen yang kuat dan tetap relevan hingga hari ini. Ia dengan berani mengajukan pertanyaan yang menjadi inti narasi Palestina: Mengapa mereka yang harus membayar harga untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan?
Namun, kekuatan buku ini sebagai sebuah polemik juga merupakan kelemahan terbesarnya jika dinilai dari standar akademis yang menuntut objektivitas. Kanafani menulis sebagai seorang partisan dalam sebuah perjuangan. Akibatnya, analisisnya memiliki beberapa keterbatasan signifikan.
Pertama, selektivitas historis. Argumennya bahwa Zionisme lahir dari privilese secara signifikan mengecilkan peran antisemitisme yang nyata dan mematikan di Eropa sebagai faktor pendorong utama. Ia memilih periode-periode toleransi dan mengabaikan berabad-abad penindasan yang membuat gagasan tentang “tempat yang aman” menjadi dambaan yang tulus bagi banyak orang Yahudi, bukan hanya elite.
Kedua, nada konspiratif. Kanafani seringkali menggambarkan perkembangan ideologi Zionis sebagai sebuah “skema kolosal” atau “konspirasi tunggal” yang terkoordinasi dengan sempurna. Ini menyederhanakan proses sejarah dan intelektual yang seringkali jauh lebih kacau, terpecah, dan penuh dengan perdebatan internal.
Ketiga, penolakan terhadap nilai artistik. Dalam fokusnya pada fungsi politik sastra, Kanafani sepenuhnya menolak kemungkinan adanya nilai artistik atau kompleksitas kemanusiaan dalam karya-karya yang ia kritik. Misalnya, kritiknya terhadap S.Y. Agnon hanya berpusat pada agenda politiknya, sambil mengabaikan sama sekali kualitas sastra yang membuatnya memenangkan Hadiah Nobel. Baginya, sebuah karya seni hanya memiliki satu fungsi: sebagai senjata ideologis.
Signifikansi yang Tak Lekang oleh Waktu
Pada akhirnya, signifikansi On Zionist Literature tidak terletak pada perannya sebagai sebuah sejarah sastra yang objektif, melainkan sebagai sebuah dokumen primer dari sebuah perjuangan naratif. Buku ini adalah manifestasi dari upaya seorang intelektual dari pihak yang terjajah untuk memahami, membongkar, dan melawan senjata paling kuat yang dimiliki oleh penjajahnya: cerita yang mereka tuturkan tentang diri mereka sendiri.
Ghassan Kanafani tidak berhasil menyelesaikan semua proyek intelektualnya; ia dibunuh dalam sebuah serangan bom mobil oleh Mossad pada tahun 1972. Namun, buku ini tetap menjadi warisan yang kuat. Kontribusinya ada dua. Pertama, ia memberikan artikulasi yang sangat penting tentang perspektif Palestina mengenai akar budaya dari perampasan tanah air mereka. Kedua, dan mungkin yang lebih universal, ia menawarkan sebuah model yang abadi tentang bagaimana melakukan kritik ideologis yang tajam—bagaimana membaca sebuah teks tidak hanya untuk apa yang dikatakannya, tetapi untuk apa yang dilakukannya. Setelah lebih dari setengah abad, di saat narasi masih menjadi medan pertempuran utama, analisis Kanafani terasa lebih relevan dari sebelumnya.
Biografi Singkat
A.R. Bahry Al Farizi, alumni Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Bekerja sebagai editor-in-chief di Pundi.or.id. Saat ini aktif sebagai Koordinator Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Kota Yogyakarta. Beberapa tulisannya pernah dimuat di Kompas.id, Media Indonesia, Republika.id., dll.