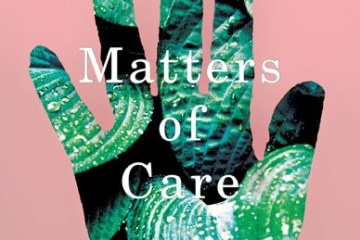Menyingkap Mitos dalam Hak Asasi Manusia
 Reinbold, Jenna. 2017. Seeing the Myth in Human Rights [Menyingkap Mitos dalam Hak Asasi Manusia]. Penerbit Universitas Pennsylvania.
Reinbold, Jenna. 2017. Seeing the Myth in Human Rights [Menyingkap Mitos dalam Hak Asasi Manusia]. Penerbit Universitas Pennsylvania.
Belum lama ini, surat edaran Mahkamah Agung terkait larangan pencatatan pernikahan beda agama ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak ahli yang merespon dengan menyayangkan hal tersebut, bahkan mengatakannya sebagai sebuah kemunduran. Pernikahan, pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia–selanjutnya ditulis HAM. Dengan adanya pelarangan ini, negara mengatur terlalu jauh terkait hak-hak dasar manusia. Jika melihat konstitusi internasional Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutya disingkat DUHAM), di pasal 16, hak manusia dewasa untuk menikah tidak dibatasi oleh apapun, termasuk agama. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya meratifikasi DUHAM, namum penjaminan HAM merupakan hak yang harus selalu dipenuhi. Batasan semacam itu menunjukkan bahwa HAM nampak hanya seperti mitos, sebagaimana diselisik oleh Jena Reinbold dalam Seeing the Myth in Human Rights (2017).
Secara umum, Reinbold dalam bukunya membahas tentang DUHAM yang memiliki sifat ke-mitos-an. Bukan maksudnya untuk merendahkan isi dan tujuan dari deklarasi, tetapi memang narasi di dalamnya terlalu menonjolkan logika yang kurang mengindahkan hak bawaan manusia. Hal yang menjadi perhatian utama adalah formulasi DUHAM dan tujuan Komisi HAM merumuskannya, juga bagaimana pemberlakuannya sebagai landasan moral dan kultural sebelum sebagai konstitusi hukum. Dibahas pula tentang adanya dua pandangan terhadap HAM. Ada ahli yang melihat HAM sebagai pragmatis, seperti politikus Ignatieff, dan ada pula yang melihat HAM sebagai suatu hal yang filosofis, seperti filsuf Derrida.
Logika Ke-mitos-an Hak Asasi Manusia
Narasi utama yang diangkat adalah mengenai pendekatan sekularisasi pada DUHAM. Ia menjelaskan kaitannya dengan kepentingan politik dilihat melalui kerangka sosio-fungsional. Analisis utamanya berinti pada deklarasi yang bersifat mythopoeic. Reinbold menggarisbawahi tentang universalitas yang secara praktis tidak realistis dan hanya ideal secara utopis. Dengan membedakan ‘produksi’ dan ‘resepsi’ yang dikaitkan dengan agama, ia banyak mengutip Durkheim sebagai landasan teoretisnya. Pandangan Durkheim mengenai agama sebagai sistem moral yang memiliki peran untuk menata ketertiban sosial diadopsi oleh deklarasi yang memiliki basis serupa sebagai fenomena manusia, namun dengan landasan yang lebih kuat. Durkheim melihat sisi sakral dari agama ini tidak dapat bersifat universal. Dalam hal ini, Reinbold memiliki pandangan yang serupa tentang DUHAM yang menurutnya universalitas hanya bagian dari mythmaking yang tidak dilandasakan pada sisi kemanusiaan.

Jenna Reinbold
Di bab pertama Reinbold menguraikan tentang teori-teori mitos dalam ranah akademik yang mendukung analisisnya pada deklarasi. Ia membagi dua antara mitos sakral dengan mitos politik. Argumen-argumen yang dibahas lebih banyak mengenai konteks historis perancangan DUHAM oleh Komisi HAM yang dikaitkan dengan diskursus sekularisme pada aspek sosial-politik dan hukum. Selain itu, narasi yang disajikan adalah mengenai saintifikasi agama di masa modern, yang di dalamnya terdapat pergeseran konsepsi agama dengan kaitannya pada manusia baik secara individual maupun komunal.
Terdapat pula dikotomi konsepsi yang membagi kategori masyarakat menjadi premodern dengan modern dan Barat dengan non-Barat. Dalam hal ini, masyarakat Barat modern yang telah menggunakan term ‘religion’ sebagai satu aspek yang diinstitusionalisasi telah memisahkan mitos sakral dengan mitos politik. DUHAM, oleh para perumusnya, dijadikan sebagai narasi otoritatif yang memisahkan diri dari agama–dan oleh karenanya menjadi sebuah mitos politik. Menurutnya mitos tidaklah harus sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal supernatural. Sifat universal dalam deklarasi yang tidak diformulasikan berdasarkan fenomena manusia yang beragam di seluruh dunia justru merupakan bagian dari mitos karena dapat memicu terjadinya bencana kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat terlebih bila implementasinya dipaksakan secara otoritatif.
DUHAM sebagai Alat Politik
Di bab selanjutnya Reinbold menjelaskan tentang karakteristik manusia dalam bingkai DUHAM yang mengesampingkan nilai sakralitas pada martabat manusia yang melekat. Telah terpampang dalam deklarasi bahwa religiusitas tidaklah merujuk pada hal-hal transedental dan berlandaskan epistemologis. Melainkan, secara retoris, deklarasi menggunakan pendekatan ontologis yang dalam preambulnya secara fundamental menekankan pada martabat manusia yang melekat. Dari hal tersebut kemudian tercipta karakteristik deklarasi sebagai unit yang sakral dalam ranah teologis maupun filosofis.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam studi agama, DUHAM terlihat memiliki dualisma antara sakral and sekular, di mana hal tersebut menjadi poin kritisi oleh para sarjana. Oleh karenanya, para teoritikus seperti Durkheim sebagai ahli terdahulu, dan Asad sebagai ahli kontemporer menaruh perhatian pada hal tersebut dan hingga kini diskursus mengenai relasi HAM dengan agama terus menjadi sebuah objek kajian.
Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada kajian teoritis dan diskursus semata, perhatian para ahli juga ditaruh pada aspek praktis khususnya terkait penerapan dari deklarasi pada institusi politik dan sosial. Secara historis, dibahas juga mengenai sakralisasi instrumen negara yang memiliki logika ke-mitos-an. Di sini, Reinbold menggunakan contoh Volksgemeinschaft pada perang Dunia II yang pada masanya dijadikan kendaraan politik untuk menindas minoritas oleh Jerman. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa esensi dari HAM melayani negara lebih dari individunya. Selain itu, bagaimana komisi HAM mengartikulasikan deklarasi nampak tidak dapat mengakomodasi perbedaan kultural antar negara sepenuhnya.
Martabat Manusia dalam Identitasnya
Bab ketiga mendemonstrasikan tentang konsep ‘keluarga-manusia’ (the human family) yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menanamkan logika sakralisasi. Hal ini berkaitan juga dengan bagaimana konsep tersebut memiliki implikasi pada perluasan deklarasi dalam proses negosiasi dan propagandanya. Dalam proses negosiasinya, penghormatan terhadap individu hanya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Barat yang menekankan pada bingkai imanen.
Berbicara secara historis, hal ini dikaitkan dengan masa pencerahan Kristen yang kemudian mempengaruhi manifestasi deklarasi yang berupa lintasan politik dengan mengedepankan prinsip ontologis. Dengan logika seperti itu, dapat diasumsikan bahwa tujuan Komisi HAM memiliki persepsi bahwa martabat manusia memiliki peran dalam membentuk identitas sosial tertentu, yang dalam deklarasi diartikulasikan sebagai ‘the human family’.
Yang dimaksud dengan ‘keluarga-manusia’ di sini adalah komunitas moral yang di dalamnya berbagi pemahaman dan aturan yang sama, dan dalam hal ini agama menjadi salah satu contoh unit keluarga-manusia. Reinbold mengumpamakan definisi agama menurut Durkheim yang memuat sakralitas yang dapat menyatukan manusia seperti halnya tujuan dari sifat universal deklarasi dengan tujuan untuk mentransformasi tatanan kehidupan sosial. Dari hal tersebut, Komisi HAM berusaha mencari hubungan yang bergantung di dalam masyarakat.
Pandangan tersebut tentu bersebrangan dengan argumentasi utilitarian yang cenderung pragmatis dan rasional karena dalam pratiknya, DUHAM tidak mampu mencegah adanya pelanggaran HAM dan penindasan. Sisi lain dari keluarga-manusia ini yaitu dapat menjembatani kehidupan sosial yang intim dengan orientasi kosmopolitanisme. Salah satunya melalui pendidikan yang dianggap dapat mencegah munculnya sikap intoleran. Maka dari itu, DUHAM tidak dapat dijadikan sebagai tujuan, melainkan hanya alat komplementer yang dapat dipakai untuk mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang.
Dimensi Ekstrayudisial DUHAM
Bab empat lebih banyak menguraikan penerapan DUHAM secara praktis khususnya sebagai payung hukum yang menjamin hak-hak mendasar yang minimum dan berlaku bagi seluruh manusia. Pada dasarnya, DUHAM tidak hanya terbatas pada konsepsi yang tersakralkan, melainkan bagaimana penegakannya dapat membangun kehidupan masyarakat yang lebih terlindungi. Meskipun dalam hal ini DUHAM memiiki karakter yang ektrayudisial dalam melihat hak mendasar manusia, namun karena kodifikasinya menggunakan bahasa hukum, maka di dalamnya mengandung diskursus hukum yang memanifestasikan kesakralannya. Berbicara mengenai sakralitas, kembali Reinbold merujuk pada Durkheim, yang dalam hal ini, ia mengeksplorasi pengembangan pemikiran Durkheim oleh sarjana kontemporer. Pendekatan sosiologis yang melihat agama sebagai tatanan moral sekaligus tatanan hukum yang memiliki sifat koersif karena sakralitasnya, tercermin dalam HAM.
Dengan sifatnya yang otoritatif dan universal, DUHAM pun memiliki persona legalitas dan yuridis. Sarjana lain mengakui kondisi tersebut sebagai kemampuan HAM yang dapat menjembatani aspek konspetual dan praktikal. Akan tetapi, Reinbold menegaskan, visi hukum DUHAM ini tidak nampak secara konkrit dan justru lebih dominan dimensi politiknya daripada dimensi hukum yang memberikan jaminan atas HAM. Terlebih dengan klaim universalitasnya yang tidak dapat menjangkau perbedaan budaya secara luas. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan re-kalibrasi diskursus pada aspek moralnya. Pergeseran tersebut akan mampu mengurai sifat hegemonik DUHAM dengan mengeksternalisasi sakralitasnya.
Di kesimpulan, Reinbold mengungkap kekurangan-kekurangan akan argumen yang menyatakan sifat ke-mitos-an dari DUHAM. Ia mencoba mendemistifikasi DUHAM dengan melihat tujuan pragmatisnya yang kadang diabaikan oleh pandangan filosofis dan melihat tujuan politiknya di balik dasar hukum yang melekat padanya. Selain itu, ia juga menawarkan padangannya bahwa DUHAM memiliki prinsip yang serupa dengan agama dari segi pembuatan mitosnya, lalu ia membantah bahwa pertentangan antara agama dan HAM selama ini tidaklah relevan. Ia merujuk pada Moyn terkait sifat ke-mitos-an pada DUHAM yang pada saat ini berkembang menjadi ‘mistik’ karena perannya yang tidak nyata dalam mencapai menjamin HAM.
Penggunaan istilah ‘myth’ dalam buku tersebut tidak memiliki maksud untuk mempeyorasikan DUHAM sebagai sesuatu yang imajinatif. Pun dengan pemahaman tentang konsep agama dalam bingkai studi agama, pengertian yang dimaksud dengan sifat ke-mitos-an di sini adalah metafora untuk lebih memahami bahwa implementasi HAM tidak dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuannya yang mensakralkan martabat manusia. Ini menjadi kritik darinya atas DUHAM yang cenderung berputar-putar di ranah diskursus dengan mengabaikan realitas politik. Ia bertumpu pada landasan sosiofungsional yang mempromosikan pentingnya HAM untuk melindungi hak individu ketimbang negara. Dengan melibatkan perspektif sarjana lain lain, analisis yang dilakukannya terhadap DUHAM merangkum kemampuan kesarjanaannya yang interdisipliner.
Sekalipun dengan bahasa yang berat dan bahasan yang kompleks, Seeing the Myth in Human Right tidak dapat disangkal mampu memberikan pemahaman baru mengenai HAM dan kaitannya dengan agama dalam kerangka akademis. Dengan penjelasan yang multidimensi, seperti filosofis, hukum, dan politis, DUHAM menjadi sebuah objek kajian yang tidak terkurung dalam diskursus retoris HAM. Kesimpulannya, Reinbold melalui karyanya tersebut menyegarkan studi agama dalam menganalisis HAM. Meskipun tidak mudah untuk mencernanya, pemikiran Reinbold menantang kita untuk dapat memperkaya pemahaman tentang sifat alami HAM dan implikasinya dalam kehidupan.