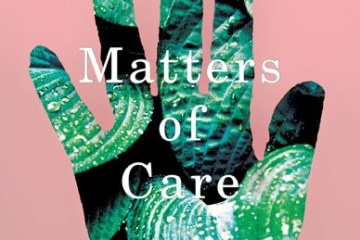Orientasi Antroposen Baru dalam Teori Sosial Keplanetan
Clark, Nigel and Bronislaw Szerszynski. 2021. Planetary Social Thought: The Anthropocene Challenge to the Social Sciences (Pemikiran Sosial Keplanetan: Tantangan Antroposen terhadap Ilmu Sosial). Penerbit Polity Press.
 Antroposen telah menjadi salah satu konsep ilmiah baru dalam lintasan skala waktu geologi terkini. Temuan ilmiah Antroposen sendiri didominasi oleh ilmu-ilmu alam terutama pendekatan geologi dengan cara mencari titik temu transisi kapan dan di mana Antroposen lahir, yang diprediksi menggantikan skala waktu sebelumnya yaitu Holosen. Seluruh akumulasi historis melalui kompleksitas aktivitas antropogenik manusia telah mengarahkan keadaan bumi yang sepenuhnya baru, bahkan tidak dapat diprediksi seperti apa konsekuensi yang akan terjadi di masa depan, sebab adanya intervensi dinamis sosial yang bergerak selaras dengan kemewaktuan geologis bumi.
Antroposen telah menjadi salah satu konsep ilmiah baru dalam lintasan skala waktu geologi terkini. Temuan ilmiah Antroposen sendiri didominasi oleh ilmu-ilmu alam terutama pendekatan geologi dengan cara mencari titik temu transisi kapan dan di mana Antroposen lahir, yang diprediksi menggantikan skala waktu sebelumnya yaitu Holosen. Seluruh akumulasi historis melalui kompleksitas aktivitas antropogenik manusia telah mengarahkan keadaan bumi yang sepenuhnya baru, bahkan tidak dapat diprediksi seperti apa konsekuensi yang akan terjadi di masa depan, sebab adanya intervensi dinamis sosial yang bergerak selaras dengan kemewaktuan geologis bumi.
Melalui buku ini, kolaborasi antara Nigel Clark (geograf) dan Bronislaw Szerszynski (sosiolog), memunculkan respons atas tantangan Antroposen sebagai sebuah jalan pendekatan alternatif bagi pendekatan multidisipliner, termasuk seni, filsafat, dan sosial humaniora. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa untuk melihat Antroposen secara lebih dekat, diperlukan pendekatan alternatif yang tidak hanya sekadar melalui pembuktiaan ilmiah perihal peristiwa alamiah semata, tetapi juga merevisi ulang pra-anggapan bahwa dimensi sosial memiliki andil yang signifikan terhadap dinamika keplanetan. Kacamata keplanetan sosial ini mengungkapkan bagaimana kuasa transformasi dunia kehidupan sosial selalu berkelindan dengan perubahan bumi secara relasional.
Ancaman perubahan iklim global semakin memprihatinkan, terlebih risiko malapetaka yang disebabkan oleh perubahan iklim ini telah melampaui tapal batas sistem kebumian sehingga mempercepat krisis ekologis; setidaknya bisa dilihat dari mencairnya lapisan es di Antartika, rusaknya ekosistem terumbu karang laut, kebakaran hutan hujan tropis, serta penurunan kualitas air dan tanah. Selama menghadapi risiko krisis global Antroposen, pertanyaan demi pertanyaan lahir sebagai bentuk tanggapan yang menyoal kecemasan eksistensial kemanusiaan, tentang sejauh mana rentang skala waktu geologi Antroposen, visi dan masa depan bumi, kelayakan huni bumi, batas-batas risiko kepunahan dan sebagainya (hlm. 3). Antroposen bukan tentang perencanaan strategis melainkan justru mendorong variasi pertanyaan filosofis yang mendalam (hlm. 4). Salah satunya ialah tentang multiplisitas keplanetan yang menantang para ilmuwan sosial humaniora untuk tidak sekadar mengklaim jargon-jargon sosiologisnya ketika membaca dimensi geologi Antroposen, begitu juga dengan ilmu alam yang hanya menganalisis Antroposen sebagai serangkaian peristiwa alam (hlm. 8). Maka, pembabakan buku ini terbagi menjadi sembilan bab dengan mempertahankan tesis pokok pemikiran tentang keplanetan sosial.
Menariknya, bab pertama buku ini dibuka dengan perkembangan diskursus ilmiah Antroposen dalam bidang geologi. Perdebatan ilmiah Antroposen semakin menarik ketika para ahli geologi mulai mempertimbangkan perubahan yang terjadi pasca revolusi industri sebagai titik balik Antroposen. Begitu juga dengan peristiwa The Great Acceleration, bumi mengalami perubahan yang sangat signifikan, tidak hanya berkaitan dengan perubahan tren laju meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didukung dengan semangat kemajuan industri baru pasca perang dunia kedua (hlm. 19).
Usaha naturalisasi Antroposen hanya melihat pada aspek kemungkinan bumi sebagai entitas alam yang tunggal dan pasti. Sementara menurut Clark and Szerszynski (2021: 31), visi keplanetan di masa depan justru harus dilihat sebagai multiplisitas—ragam kapasitas sosial dan geologis untuk melihat swa-diferensiasi dan transformasi—ketika memahami eksistensi keplanetan bumi selanjutnya. Multiplisitas ini memberikan dampak pemahaman bahwa manusia tidak hanya sebagai sentra perubahan struktur sejarah geologi semata, tetapi juga sebaliknya, krisis saat ini memberikan hambatan bagi pertumbuhan dan pembangunan sosial dunia ketiga.
Perlawanan dominasi narasi tunggal Antroposen yang sangat bergantung pada pembuktian jejak geologis melalui pendekatan ilmu alam mendapatkan reaksi dari kalangan ilmuwan sosial dan humaniora. Menariknya, bagian bab kedua memberikan sudut pandang kritis mengenai status ilmu sosial yang seharusnya berani melakukan gebrakan sekaligus respons terhadap krisis Antroposen atau yang disebut sebagai ‘socialize the Anthropocene’, yakni membumikan kembali Antroposen ke level pertanyaan fundamental tentang kekuasaan, pengetahuan, dan diversitas sosial (hlm. 38).
Di sisi lain, pertimbangan status ontologis manusia sebagai agen geologi turut serta mendorong kembali pertimbangan pertanyaan pembalikan melalui perspektif ‘geologizing the social’, yakni mempertanyakan siapa yang berhak berbicara tentang bumi. Artinya, posisi ini menarik manifestasi kuasa sosial yang tidak hanya sekadar ekspresi kehidupan-sosial melainkan juga bagian dari daya kausal serta properti bumi (hlm. 46). Penyetaraan perspektif antara dimensi sosial dan dimensi geologi ini merupakan pendekatan onto-epistemologis yang bertujuan untuk memberikan titik temu atas jurang keterpisahan epistemik warisan semangat modernitas. Kuasa sosial akan selalu bertopang dengan beragam properti ekologis bumi, dan begitu juga sebaliknya, masa depan bumi akan selalu dipengaruhi oleh putusan-putusan dunia sosial.
Bab ketiga buku ini menjelaskan bagaimana konsensus dan konvensi sosial, seperti halnya pembagian kerja maupun gender, juga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kacamata keplanetan. Clark dan Szerszynski (2021) melacak ulang bahwa perkembangan dimensi geologis berbanding lurus dan saling mempengaruhi sepanjang sejarah peradaban manusia. Sejak adanya peningkatan tren sosio-ekonomi The Great Acceleration, kemajuan mesin dan teknologi rumah tangga mendukung kerja domestik secara lebih efektif dan efisien (hlm. 58-60). Pekerjaan rumah tangga yang dianggap remeh temeh ternyata memiliki konsekuensi keplanetan, mulai dari pekerjaan dapur seperti memasak, mencuci, dan bahkan menyetrika. Semua pekerjaan rumah tangga ini senantiasa melibatkan persediaan sumber daya alam, terutama energi berbahan bakar fosil dalam jumlah yang sangat besar (hlm. 65). Meskipun demikian, ini bukan berarti pengaruh trajektori Antroposen hanya dipengaruhi oleh salah satu kelas atau gender tertentu, tetapi sebaliknya, arah gerak Antroposen ini berdasarkan pada tindakan masif kolektif masyarakat dunia.
Bab keempat buku ini mulai merumuskan ulang pemikiran kritis keplanetan sosial. Langkah pemikiran reflektif mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa manusia tidak mungkin lagi mampu mengembalikan keseimbangan planet bumi secara utuh (hlm. 81). Manusia hari ini berhadapan dengan apa yang telah dan sedang-akan terjadi. Seluruh krisis ekologis serta ketersisaan sumber daya alam yang ada membuka satu diskusi filosofis tentang multiplisitas keplanetan (‘planetary multiplicity’) sebagai salah satu metode yang dibutuhkan masyarakat global ketika menghadapi malapetaka geo-sosial yang diakibatkan oleh keretakan Antroposen di masa depan.
Berdasarkan multisiplitas keplanetan maka bumi harus dipahami bukan lagi sebagai latar belakang material yang pasif tetapi memiliki dualitas yang mampu mengorganisir ‘dirinya’ sendiri sekaligus mempengaruhi seluruh dimensi praktis sosial secara dinamis (hlm. 90). Pembuktian ini tercermin dari beragam perbedaan pemahaman karakteristik realitas bumi yang sangat bergantung pada ‘pengetahuan yang tersituasikan’ dengan ‘kondisi planet bumi’ tertentu (hlm. 91). Kita dapat membayangkan bahwa pada masa revolusi industri awal, masyarakat cenderung tidak memikirkan akibat dari eksploitasi alam berkat semangat penjelajahan modern. Namun, pada fase memasuki dekade abad ke-21, yakni ketika sumber daya alam semakin langka, kesadaran ekologis masyarakat semakin meningkat berkat adanya ancaman malapetaka tak terduga, seperti kepunahan massal, pandemi, krisis air dan bahan bakar, pemanasan global, perubahan iklim, dan sebagainya.
Bab kelima dan keenam merujuk pada kelemahan dari visi filsafat dan ilmu modern yang berkembangan sekitar abad ke-18 dan ke-19, yang membawa katastropi ekologi sebab adanya semangat eksplorasi dunia lama ke dunia baru (hlm. 105). Kolonisasi juga memiliki peran terhadap marginalisasi berdasarkan ras sebagaimana penindasan terhadap masyarakat di luar kulit putih (misal stigma warna kulit cokelat atau hitam) yang dianggap sebagai ‘yang-lain’, masyarakat tidak beradab yang harus dimajukan (hlm. 113). Meskipun demikian, imajinasi kemajuan modern yang dibawa untuk dunia baru justru membawa penindasan dan eksploitasi, tidak hanya terhadap masyarakat pribumi tetapi juga ‘kekerasan’ terhadap kultur dan alamnya. Studi historis tentang mobilitas sumber daya, artefak, dan manusia ditujukan untuk mengungkap bentuk dari kemajuan suatu peradaban (hlm. 126).
Ekspedisi zaman purba, kebudayaan Yamnaya, telah membuka jalur transportasi baru, termasuk penaklukan hewan-hewan liar, antara lain: kuda, banteng, kerbau, sapi, yang digunakan untuk membawa barang dan mengembangkan pola nomaden yang lebih maju (hlm. 143). Pra-kondisi Antroposen antik ini semakin berkembang ketika terjadinya revolusi mobilitas, tidak hanya perpindahan antara manusia tetapi juga pergerakan objek material geologis (misal: rempah, minyak bumi, batu bara). Ketergantungan terhadap bahan baku material alam ini bagaimanapun juga akan dikembalikan untuk siklus aktivitas mobilitas masyarakat dunia selanjutnya, bukan untuk alam itu sendiri. Dengan demikian, tantangan manusia global selanjutnya menyoal mobilitas/perpindahan yang semakin terancam karena adanya krisis lanskap jalur transportasi, baik jalur darat, air, dan udara, serta semakin rapuhnya batas-batas kewilayahan geografis alamiah.
Bab ketujuh buku ini memiliki tarik ulurnya dengan bab kelima sebelumnya, mengambil salah satu contoh praktik rezim ekstraktivisme, yakni penambangan mineral yang semakin memperparah siklus fosfor global selanjutnya. Strategi yang dilakukan adalah melalui visi sekularisasi ilmu pengetahuan Barat sebagai jalan untuk mematahkan semangat tradisional pribumi dalam menjaga alamnya (hlm. 153). Clark dan Szerszynski (2021) mengritik rezim ekstraktivisme yang tersebar di wilayah Selandia Baru, Australia, Amerika Latin, dan tempat lainnya. Untuk melawan represi pengetahuan ini, diperlukan semacam strategi ontologi-politik yang mampu mendobrak struktur pemikiran modernitas ‘universal’ dengan mempertimbangkan keragaman dunia-yang mungkin atau ‘pluriverse’. Selanjutnya, Clark dan Szerszynski (2021) mengakhiri buku ini dengan memberikan setidaknya sepuluh pertanyaan pamungkas lanjutan tentang kemungkinan berbagai macam tantangan keplanetan sosial di masa depan beserta kemungkinan gerakan praksis untuk mengatasi dilema atas kompleksitas masalah sosial-global beserta ancaman malapetaka krisis keplanetan.
Buku ‘Planetary Social Thought’ menjadi salah satu pengantar awal untuk memahami kompleksitas dimensi Antroposen teruntuk para pemikir, cendikiawan, maupun peneliti, baik dalam dunia akademik maupun sebagai putusan kebijakan publik. Meskipun Antroposen belum diratifikasi secara formal oleh para ahli geologi, tantangan Antroposen dewasa ini selalu berkelindan dengan pertanyaan masa lalu sekaligus masa depan. Dominasi regulasi norma masyarakat global hari ini mengatur banyak hal termasuk ‘imaji takdir’ masa depan bumi. Padahal, krisis global saat ini terjadi akibat adanya rezim ‘universalis’ warisan masa lalu yang selalu melanggengkan kuasa eksploitasi, tidak hanya terhadap manusia tetapi juga bumi. Clark dan Szerszynski mengklaim bahwa dekolonisasi bumi juga diperlukan untuk membuka kemungkinan imajinasi sosial secara multi bahkan pluriversalistik. Dengan demikian, buku ini memberikan pandangan alternatif bagi para peneliti, terutama lintas disiplin, untuk memberanikan diri supaya menginvestigasi lebih lanjut ragam dimensi-dimensi tersembunyi dari Antroposen. Orientasi sosial keplanetan kemudian akan selalu berhadapan dengan kerumitan dunia-kehidupan sosial, polemik kepentingan lokal-global, dan determinasi kuat bumi yang akan senantiasa berbanding lurus dengan ‘pilihan takdir’ lintasan Antroposen.